Masih seputar suasana kelabu di hari-hari wafatnya Sukarno, Sang Proklamator. Ini tentang bagaimana para istri dan mantan istri presiden yang gallant itu bereaksi, bersikap, dan bertutur ihwal kepergian lelaki yang begitu dipuja. Ternyata, sekalipun memiliki perasaan yang sama dalam hal cinta, tetapi berbeda-beda ekspresi mereka menerima kematian mantan suami atau suami mereka.
Inggit Garnasih, istri kedua Sukarno yang dinikahi tahun 1923, adalah wanita yang dengan setia mengikuti dan mendukung perjuangan Sukarno sejak usia 21 tahun. Ia bahkan turut serta dalam setiap pengasingan Bung Karno, mulai dari Ende sampai Bengkulu. Ia lahir tahun 1888, lebih tua 12 tahun dari Bung Karno. Itu artinya, saat “nKus” panggilan kesayangan Inggit kepada Bung Karno, wafat, usia Inggit 82 tahun.
Nah, di usia yang sepuh, dan dalam kondisi sakit… ia menerima berita duka pada hari Minggu, 21 Juni 1970. Ia tergopoh-gopoh berangkat dari Bandung menuju Jakarta, ditemani putri angkatnya, Ratna Juami. Dalam batin, ia harus memberi penghormatan kepada mantan suami yang telah ia antar ke pintu gerbang kemerdekaan.
Setiba di Wisma Yaso, di tengah lautan massa yang berjubel, berbaris, antre hendak memberi penghormatan terakhir, Inggit –tentu saja– mendapat keistimewaan untuk segera diantar mendekat ke peti jenazah. Di dekat tubuh tak bernyawa di hadapannya, Inggit berucap, “Ngkus, geuning Ngkus tehmiheulan, ku Inggit di doakeun…” (Ngkus, kiranya Ngkus mendahului, Inggit doakan….). Sampai di situ, suaranya terputus, kerongkongan terasa tersumbat. Badannya yang sudah renta dan lemah, terhuyung diguncang perasaan sedih. Sontak, Ibu Wardoyo, kakak kandung Bung Karno (nama aslinya Sukarmini) memapah tubuh tua Inggit.

Lain lagi Fatmawati, istri ketiga Bung Karno yang pergi meninggalkan Istana setelah Bung Karno menikahi Hartini. Ia adalah sosok perempuan yang teguh pendirian. Ia sudah bertekad tidak akan datang ke Wisma Yaso. Karenanya, begitu mengetahui ayah dari lima putra-putrinya telah meninggal, ia segera memohon kepada Presiden Soeharto agar jenazah suaminya disemayamkan di rumahnya di Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, meski sebentar. Sayang, Soeharto menolak permintaan Fatmawati.
Hati Fatma benar-benar galau. Antara jerit hati ingin melihat wajah suami untuk terakhir kali, dengan keteguhan prinsip. Bahkan, putra-putrinya pun tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Fatma untuk tetap tinggal di rumah. Meski, atas kesepakatan semua pihak, peti jenazah tidak ditutup hingga batas akhir jam 24.00, dengan harapan, Fatma datang pada detik-detik terakhir. Apa hendak dikata, Fatma tak juga tampak muka.
Pengganti kehadiran Fatma, adalah sebuah karangan bunga dari si empunya nama. Dengan kalimat pendek dan puitis, Fatma menuliskan pesan, “Tjintamu yang menjiwai hati rakyat, tjinta Fat”… Sungguh mendebarkan kalimat itu, bagi siapa pun yang membacanya.

Bagaimana pula dengan Hartini? Ah… melihat Hartini, hanya duka dan duka sepanjang hari. Wajah cantik keibuan, mengguratkan kelembutan. Sinar matanya penuh kasih sayang… Ia tak henti menangis. Hartini, salah satu istri yang begitu dicintai Sukarno, sehingga dalam testamennya, Sukarno menghendaki agar jika mati, Hartini dimakamkan di dekat makamnya. Ia ingin selalu dekat Hartini, wanita lembut keibuan yang dinikahinya Januari 1952.
Kebetulan, Hartini pula yang paling intens merawat dan menemani Bung Karno hingga akhir hayatnya. Sampai-sampai, Rachmawati, salah satu putri Bung Karno yang kebetulan juga paling intens menemani bapaknya di hari-hari akhir kehidupannya, memuji Hartini sebagai istri yang sangat setia dan baik hati. Rachma yang semula berperasaan tidak menyukai Hartini –dan ini wajar saja– menjadi dekat dan akrab dengan Hartini.
Semula, Rachma hanya berpura-pura baik dengan Hartini di depan bapaknya. Sebab, Rachma tahu betul, bapaknya begitu senang jika ada Hartini di dekatnya. Bapaknya begitu mencintai Hartini. Dan… dengan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian tulus Hartini kepada Bung Karno di hari-hari akhir hidupnya, sontak membuka mata hati Rachma tentang sosok Hartini. Sejak itulah tumbuh keakraban dan kecintaan Rachma kepada Ibu Hartini.

Lain Inggit, beda Fatma, dan tak sama pula sikap Hartini… adalah ekspresi imported wife, si jelita Ratna Sari Dewi, wanita Jepang benama asli Naoko Nemoto. Wanita kelahiran tahun 1940 yang dinikahi Bung Karno 3 Maret 1962 itu memang dikenal lugas. Ia datang ke Jakarta bersama Kartika Sari (4 th) pada tanggal 20 Juni 1970 pukul 20.20 malam. Mengetahui suaminya lunglai tak berdaya, dirawat dalam penjagaan ketat tak manusiawi.
Hati Dewi teriris, terlebih bila mengingat anaknya sama sekali belum pernah berjumpa dengan ayahnya. Dalam catatan, Dewi pernah berkunjung ke Wisma Yaso saat hamil, tapi tentara melarangnya masuk. Dewi marah, karena kesulitan yang dialaminya. Ia, sebagai istri sah Sukarno, tidak bisa leluasa menengok apalagi menemani hari-hari Sukarno yang sedang bergulat dengan maut.
Latar belakang budaya yang berbeda, membuat Dewi kelihatan sangat vokal pada zamannya. Ia pernah marah besar kepada Soeharto dengan melontarkan ucapan pedas melalui surat terbuka tanggal 16 April 1970.
Begini sebagian isi surat itu:
“Tuan Soeharto, Bung Karno itu saya tahu benar-benar sangat mencintai Indonesia dan rakyatnya. Sebagai bukti bahwa meskipun ada lawannya yang berkali-kali menteror beliau, beliau pun masih mau meberikan pengampunan kalau yang bersangkutan itu mau mengakui kesalahannya. Dibanding dengan Bung Karno, maka ternyata di balik senyuman Tuan itu, Tuan mempunyai hati yang kejam. Tuan telah membiarkan rakyat, yaitu orang-orang PKI dibantai. Kalau saya boleh bertanya, ‘Apakah Tuan tidak mampu dan tidak mungkin mencegahnya dan melindungi mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah?”
Bukan hanya itu. Penampilan Dewi yang masih tampak begitu cantik di suasana duka, seperti menjadi icon. Terlebih dengan keterbukaan sikapnya. Seperti saat dengan penuh emosi ia melabrak Harjatie, istri Bung Karno yang telah diceraikan itu, sebagai seorang istri yang menyia-nyiakan Bung Karno, menuduh Harjatie meninggalkan Sukarno di masa-masa sulit. Harjatie pun menangis, dan bergerak meninggalkan tempat itu.
Begitulah, empat dari (setidaknya) delapan wanita yang pernah diperistri Bung Karno. Sama dalam mencinta, beda dalam mengekspresikan duka.
Soeharto Datang, Setelah Bung Karno “Terbang”
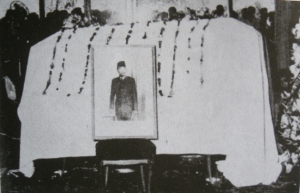
Akses informasi yang terbatas, penjagaan yang sangat ketat, mengakibatkan tidak satu pun wartawan dapat mengikuti hari-hari terakhir Bung Karno, baik ketika masih dalam perawatan, maupun ketika Bung Karno mangkat. Satu-satunya informasi yang secara terbuka didapat wartawan ketika itu adalah pengumuman resmi tim dokter ihwal meninggalnya Ir. Sukarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi hari 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Sejurus kemudian, jenazah Bung Karno dibawa ke Wisma Yaso, rumah Dewi Sukarno (sekarang Museum Satria Mandala). Wisma yang tak berpenghuni beberapa hari terakhir, sangat menyedihkan keadaannya. Sementara itu, masyarakat ibukota yang sudah mendengar berita kematian Bung Karno, berjejal merangsek ke arah Wisma Yaso, hendak memberi penghormatan terakhir kepada tokoh yang dikagumi dan dicintai.

Tak luput, Presiden Soeharto dan Ibu Tien juga hadir di sana. Sebelumnya, pukul 07.30, atau 30 menit setelah berpulangnya Bung Karno ke Rahmatullah, Soeharto dan Ibu Tien datang ke RSPAD. Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan, “Waktu saya mendengar beliau meninggal pada tanggal 21 Juni 1970, cepat saya menjenguknya di rumah sakit. Setelah itu barulah aku berpikir mengenai pemakamannya”. Dan hari itu, menjadi pertemuan terakhir setelah Soeharto menjatuhkan Bung Karno, dan tidak menemuinya lagi sejak 1967.

Sebelumnya, Soeharto hanya menyadap berita kematian Sukarno dari para petugas. Dalam beberapa kesempatan, sikap Soeharto terhadap Sukarno dikatakannya sebagai “mikul dhuwur, mendem jero”. Falsafah Jawa itu sejatinya mulia, karena mengandung makna menghormati setinggi-tingginya, dan menyimpan atau mengubur aib sedalam-dalamnya. Falsafah itu oleh Soeharto diartikan dengan mengasingkan Sukarno, dan “membunuhnya” pelan-pelan dalam kerangkengan kejam di Wisma Yaso hingga menjelang ajal.
Tanggal 22 Juni, atau sehari setelah kematiannya, jenazah Sukarno dibawa ke Blitar, Jawa Timur lewat Malang. Sholat jenazah sudah dilakukan malamnya, dengan imam Menteri Agama KH Achmad Dahlan, sedang sholat jenazah oleh rakyat, diimami Buya Hamka.

Masih menurut buku TRAGEDI SUKARNO tulisan Reni Nuryanti, ada catatan menarik lain tentang makam Sukarno, yang ternyata hanya dimakamkan di bekas Taman Makam Pahlawan Bahagia Sentul. Nah, ihwal dimakamkannya jenazah Sukarno di Blitar, Soeharto berdalih, adanya dua kehendak, antara permintaan almarhum Bung Karno agar dimakamkan di Bogor, dan keinginan keluarga yang berbeda-beda. Karena itulah akhirnya diputuskan dimakamkan di Blitar.
Banyak pihak menduga, keputusan Soeharto itu sarat politik. Ia tidak menghiraukan testamen atau permintaan ahli kubur bernama Ir. Sukarno, Presiden RI pertama yang menghendaki jika meninggal, minta dimakamkan di Bogor. Para pihak menduga, ada kepentingan jangka panjang dari Soeharto untuk “mengubur lebih dalam” Sukarno beserta nama besar dan kecintaan rakyat kepadanya. Inilah yang di kemudian hari disebut sebagai “desukarnoisasi”, upaya menghapus nama Sukarno dari memori rakyat Indonesia.
Sebaliknya, jika jazad Bung Karno dimakamkan di Bogor, sama saja menghambat langkah Soeharto untuk menenggelamkan nama besar Sukarno. Jarak Bogor – Jakarta terlalu dekat, sehingga kenangan rakyat tetap melekat. Ini yang secara politis akan mengganggu kewibawaannya. Langkah dan kebijakan untuk melarang semua ajaran Sukarno, langkah menjebloskan 0rang-orang dekat Sukarno ke dalam tahanan tanpa pengadilan, adalah bentuk lain dari upaya Soeharto benar-benar menghabisi Sukarno.
Satu hal yang Soeharto lupa, bahwa kebenaran senantiasa akan mengalir menemukan jalannya sendiri. Sekalipun kebenaran itu sudah dibelokkan. Sekalipun kebenaran itu sudah disumbat. Sekalipun kebenaran itu sudah dikubur dalam-dalam. Dan… kebenaran niscaya akan mengalir dalam sungainya sejarah. (roso daras)

Ratna Sari Dewi menatap jenazah suaminya. Tampak di belakang, Rachmawati, Megawati, Sukmawati.

Rakyat berjejal memberi penghormatan terakhir kepada Bung Karno. Sementara, sepasukan tentara berjaga-jaga dengan ketat dan senapan di tangan.
Terima kasih, ya Tuhan, Engkau telah memberi kami seorang manusia Sukarno yang telah lahir dalam permulaan abad ke-20, dan membebaskan bangsa ini dari penjajah. (roso daras)Inggit Garnasih, istri kedua Sukarno yang dinikahi tahun 1923, adalah wanita yang dengan setia mengikuti dan mendukung perjuangan Sukarno sejak usia 21 tahun. Ia bahkan turut serta dalam setiap pengasingan Bung Karno, mulai dari Ende sampai Bengkulu. Ia lahir tahun 1888, lebih tua 12 tahun dari Bung Karno. Itu artinya, saat “nKus” panggilan kesayangan Inggit kepada Bung Karno, wafat, usia Inggit 82 tahun.
Nah, di usia yang sepuh, dan dalam kondisi sakit… ia menerima berita duka pada hari Minggu, 21 Juni 1970. Ia tergopoh-gopoh berangkat dari Bandung menuju Jakarta, ditemani putri angkatnya, Ratna Juami. Dalam batin, ia harus memberi penghormatan kepada mantan suami yang telah ia antar ke pintu gerbang kemerdekaan.
Setiba di Wisma Yaso, di tengah lautan massa yang berjubel, berbaris, antre hendak memberi penghormatan terakhir, Inggit –tentu saja– mendapat keistimewaan untuk segera diantar mendekat ke peti jenazah. Di dekat tubuh tak bernyawa di hadapannya, Inggit berucap, “Ngkus, geuning Ngkus tehmiheulan, ku Inggit di doakeun…” (Ngkus, kiranya Ngkus mendahului, Inggit doakan….). Sampai di situ, suaranya terputus, kerongkongan terasa tersumbat. Badannya yang sudah renta dan lemah, terhuyung diguncang perasaan sedih. Sontak, Ibu Wardoyo, kakak kandung Bung Karno (nama aslinya Sukarmini) memapah tubuh tua Inggit.

Lain lagi Fatmawati, istri ketiga Bung Karno yang pergi meninggalkan Istana setelah Bung Karno menikahi Hartini. Ia adalah sosok perempuan yang teguh pendirian. Ia sudah bertekad tidak akan datang ke Wisma Yaso. Karenanya, begitu mengetahui ayah dari lima putra-putrinya telah meninggal, ia segera memohon kepada Presiden Soeharto agar jenazah suaminya disemayamkan di rumahnya di Jl. Sriwijaya, Kebayoran Baru, meski sebentar. Sayang, Soeharto menolak permintaan Fatmawati.
Hati Fatma benar-benar galau. Antara jerit hati ingin melihat wajah suami untuk terakhir kali, dengan keteguhan prinsip. Bahkan, putra-putrinya pun tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Fatma untuk tetap tinggal di rumah. Meski, atas kesepakatan semua pihak, peti jenazah tidak ditutup hingga batas akhir jam 24.00, dengan harapan, Fatma datang pada detik-detik terakhir. Apa hendak dikata, Fatma tak juga tampak muka.
Pengganti kehadiran Fatma, adalah sebuah karangan bunga dari si empunya nama. Dengan kalimat pendek dan puitis, Fatma menuliskan pesan, “Tjintamu yang menjiwai hati rakyat, tjinta Fat”… Sungguh mendebarkan kalimat itu, bagi siapa pun yang membacanya.

Bagaimana pula dengan Hartini? Ah… melihat Hartini, hanya duka dan duka sepanjang hari. Wajah cantik keibuan, mengguratkan kelembutan. Sinar matanya penuh kasih sayang… Ia tak henti menangis. Hartini, salah satu istri yang begitu dicintai Sukarno, sehingga dalam testamennya, Sukarno menghendaki agar jika mati, Hartini dimakamkan di dekat makamnya. Ia ingin selalu dekat Hartini, wanita lembut keibuan yang dinikahinya Januari 1952.
Kebetulan, Hartini pula yang paling intens merawat dan menemani Bung Karno hingga akhir hayatnya. Sampai-sampai, Rachmawati, salah satu putri Bung Karno yang kebetulan juga paling intens menemani bapaknya di hari-hari akhir kehidupannya, memuji Hartini sebagai istri yang sangat setia dan baik hati. Rachma yang semula berperasaan tidak menyukai Hartini –dan ini wajar saja– menjadi dekat dan akrab dengan Hartini.
Semula, Rachma hanya berpura-pura baik dengan Hartini di depan bapaknya. Sebab, Rachma tahu betul, bapaknya begitu senang jika ada Hartini di dekatnya. Bapaknya begitu mencintai Hartini. Dan… dengan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian tulus Hartini kepada Bung Karno di hari-hari akhir hidupnya, sontak membuka mata hati Rachma tentang sosok Hartini. Sejak itulah tumbuh keakraban dan kecintaan Rachma kepada Ibu Hartini.

Lain Inggit, beda Fatma, dan tak sama pula sikap Hartini… adalah ekspresi imported wife, si jelita Ratna Sari Dewi, wanita Jepang benama asli Naoko Nemoto. Wanita kelahiran tahun 1940 yang dinikahi Bung Karno 3 Maret 1962 itu memang dikenal lugas. Ia datang ke Jakarta bersama Kartika Sari (4 th) pada tanggal 20 Juni 1970 pukul 20.20 malam. Mengetahui suaminya lunglai tak berdaya, dirawat dalam penjagaan ketat tak manusiawi.
Hati Dewi teriris, terlebih bila mengingat anaknya sama sekali belum pernah berjumpa dengan ayahnya. Dalam catatan, Dewi pernah berkunjung ke Wisma Yaso saat hamil, tapi tentara melarangnya masuk. Dewi marah, karena kesulitan yang dialaminya. Ia, sebagai istri sah Sukarno, tidak bisa leluasa menengok apalagi menemani hari-hari Sukarno yang sedang bergulat dengan maut.
Latar belakang budaya yang berbeda, membuat Dewi kelihatan sangat vokal pada zamannya. Ia pernah marah besar kepada Soeharto dengan melontarkan ucapan pedas melalui surat terbuka tanggal 16 April 1970.
Begini sebagian isi surat itu:
“Tuan Soeharto, Bung Karno itu saya tahu benar-benar sangat mencintai Indonesia dan rakyatnya. Sebagai bukti bahwa meskipun ada lawannya yang berkali-kali menteror beliau, beliau pun masih mau meberikan pengampunan kalau yang bersangkutan itu mau mengakui kesalahannya. Dibanding dengan Bung Karno, maka ternyata di balik senyuman Tuan itu, Tuan mempunyai hati yang kejam. Tuan telah membiarkan rakyat, yaitu orang-orang PKI dibantai. Kalau saya boleh bertanya, ‘Apakah Tuan tidak mampu dan tidak mungkin mencegahnya dan melindungi mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah?”
Bukan hanya itu. Penampilan Dewi yang masih tampak begitu cantik di suasana duka, seperti menjadi icon. Terlebih dengan keterbukaan sikapnya. Seperti saat dengan penuh emosi ia melabrak Harjatie, istri Bung Karno yang telah diceraikan itu, sebagai seorang istri yang menyia-nyiakan Bung Karno, menuduh Harjatie meninggalkan Sukarno di masa-masa sulit. Harjatie pun menangis, dan bergerak meninggalkan tempat itu.
Begitulah, empat dari (setidaknya) delapan wanita yang pernah diperistri Bung Karno. Sama dalam mencinta, beda dalam mengekspresikan duka.
Soeharto Datang, Setelah Bung Karno “Terbang”
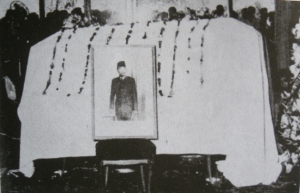
Akses informasi yang terbatas, penjagaan yang sangat ketat, mengakibatkan tidak satu pun wartawan dapat mengikuti hari-hari terakhir Bung Karno, baik ketika masih dalam perawatan, maupun ketika Bung Karno mangkat. Satu-satunya informasi yang secara terbuka didapat wartawan ketika itu adalah pengumuman resmi tim dokter ihwal meninggalnya Ir. Sukarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi hari 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Sejurus kemudian, jenazah Bung Karno dibawa ke Wisma Yaso, rumah Dewi Sukarno (sekarang Museum Satria Mandala). Wisma yang tak berpenghuni beberapa hari terakhir, sangat menyedihkan keadaannya. Sementara itu, masyarakat ibukota yang sudah mendengar berita kematian Bung Karno, berjejal merangsek ke arah Wisma Yaso, hendak memberi penghormatan terakhir kepada tokoh yang dikagumi dan dicintai.

Tak luput, Presiden Soeharto dan Ibu Tien juga hadir di sana. Sebelumnya, pukul 07.30, atau 30 menit setelah berpulangnya Bung Karno ke Rahmatullah, Soeharto dan Ibu Tien datang ke RSPAD. Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan, “Waktu saya mendengar beliau meninggal pada tanggal 21 Juni 1970, cepat saya menjenguknya di rumah sakit. Setelah itu barulah aku berpikir mengenai pemakamannya”. Dan hari itu, menjadi pertemuan terakhir setelah Soeharto menjatuhkan Bung Karno, dan tidak menemuinya lagi sejak 1967.

Sebelumnya, Soeharto hanya menyadap berita kematian Sukarno dari para petugas. Dalam beberapa kesempatan, sikap Soeharto terhadap Sukarno dikatakannya sebagai “mikul dhuwur, mendem jero”. Falsafah Jawa itu sejatinya mulia, karena mengandung makna menghormati setinggi-tingginya, dan menyimpan atau mengubur aib sedalam-dalamnya. Falsafah itu oleh Soeharto diartikan dengan mengasingkan Sukarno, dan “membunuhnya” pelan-pelan dalam kerangkengan kejam di Wisma Yaso hingga menjelang ajal.
Tanggal 22 Juni, atau sehari setelah kematiannya, jenazah Sukarno dibawa ke Blitar, Jawa Timur lewat Malang. Sholat jenazah sudah dilakukan malamnya, dengan imam Menteri Agama KH Achmad Dahlan, sedang sholat jenazah oleh rakyat, diimami Buya Hamka.

Masih menurut buku TRAGEDI SUKARNO tulisan Reni Nuryanti, ada catatan menarik lain tentang makam Sukarno, yang ternyata hanya dimakamkan di bekas Taman Makam Pahlawan Bahagia Sentul. Nah, ihwal dimakamkannya jenazah Sukarno di Blitar, Soeharto berdalih, adanya dua kehendak, antara permintaan almarhum Bung Karno agar dimakamkan di Bogor, dan keinginan keluarga yang berbeda-beda. Karena itulah akhirnya diputuskan dimakamkan di Blitar.
Banyak pihak menduga, keputusan Soeharto itu sarat politik. Ia tidak menghiraukan testamen atau permintaan ahli kubur bernama Ir. Sukarno, Presiden RI pertama yang menghendaki jika meninggal, minta dimakamkan di Bogor. Para pihak menduga, ada kepentingan jangka panjang dari Soeharto untuk “mengubur lebih dalam” Sukarno beserta nama besar dan kecintaan rakyat kepadanya. Inilah yang di kemudian hari disebut sebagai “desukarnoisasi”, upaya menghapus nama Sukarno dari memori rakyat Indonesia.
Sebaliknya, jika jazad Bung Karno dimakamkan di Bogor, sama saja menghambat langkah Soeharto untuk menenggelamkan nama besar Sukarno. Jarak Bogor – Jakarta terlalu dekat, sehingga kenangan rakyat tetap melekat. Ini yang secara politis akan mengganggu kewibawaannya. Langkah dan kebijakan untuk melarang semua ajaran Sukarno, langkah menjebloskan 0rang-orang dekat Sukarno ke dalam tahanan tanpa pengadilan, adalah bentuk lain dari upaya Soeharto benar-benar menghabisi Sukarno.
Satu hal yang Soeharto lupa, bahwa kebenaran senantiasa akan mengalir menemukan jalannya sendiri. Sekalipun kebenaran itu sudah dibelokkan. Sekalipun kebenaran itu sudah disumbat. Sekalipun kebenaran itu sudah dikubur dalam-dalam. Dan… kebenaran niscaya akan mengalir dalam sungainya sejarah. (roso daras)

Ratna Sari Dewi menatap jenazah suaminya. Tampak di belakang, Rachmawati, Megawati, Sukmawati.

Rakyat berjejal memberi penghormatan terakhir kepada Bung Karno. Sementara, sepasukan tentara berjaga-jaga dengan ketat dan senapan di tangan.
Pemakaman Bung Karno

Rakyat Indonesia dari penjuru Tanah Air, berjubel, tidak saja di sekitar Wisma Yaso tempat jenazah Bung Karno disemayamkan, tetapi juga di Blitar, Jawa Timur, tempat jazad Bung Karno dikebumikan. Seperti pengalaman pribadi mantan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko. Ia merasa bagai tersambar petis demi mendengar kematian tokoh bangsa yang delapan tahun ia layani. Bambang yang ketika Bung Karno wafat sudah menjabat sebagai Asisten Kepala Personil Urusan Militer Mabes TNI-AL itu, bergegas menuju Wisma Yaso.
Wisma Yaso yang sejak siang sudah dijejali kerumunan rakyat yang hendak melayat, tidak juga surut hingga malam hari. Bambang pun masuk dalam antrian pelayat, yang berjalan menuju ruang tengah Wisma Yaso setapak demi setapak. Suasana ketika itu dilukiskan sebagai sangat mengharukan. Tidak terdengar percakapan, kecuali isak tangis, dan bisik-bisik pelayat. Di sudut ruang, masih tampak kerabat dan pelayat yang tak kuasa menahan jeritan hati yang mendesak di rongga dada, hingga tampak tersedu-sedu.
Tiba di dekat peti jenazah, Bambang melantunkan doa, “Ya Tuhan, Engkau telah berkenan memanggil kembali putraMu, Bung Karno. Terimalah kiranya arwah beliau di sisiMu. Sudilah Engkau mengampuni segala dosa-dosanya dan berkenanlah Engkau menerima segala tekad dan perbuatannya yang baik. Engkau Mahatahu ya Tuhan, dan Engkaulah Mahakuasa, aku mohon kabulkanlah doaku ini. Amin”
Segera setelah usai berdoa, Bambang menuju kamar lain, tempat keluarga BK berkumpul. Di sana tampak Hartini, Dewi, Guntur, Mega, Rachma, Sukma, Guruh, Bayu, dan Taufan. Mereka pun saling berangkulan. Sejurus kemudian, Sekmil Presiden, Tjokropranolo mendekati Bambang dan berkata, “Mas Bambang, kami mohon sedapatnya bantulah kami dalam menjaga dan melayani keluarga BK yang saat ini amat sedih dan emosional.” Bambang segera menukas, “Baik, tapi toong sampaikan hal ini kepada KSAL.”
Begitulah. Bambang sejak itu tak pernah jauh dari keluarga Bung Karno. Baginya, inilah bhakti terakhir yang dapat ia persembahkan bagi Bung Karno. Bambang juga berada di mobil bersama keluarga Bung Karno dalam perjalanan dari Wisma Yaso ke Halim, dari Halim terbang ke Malang, dan dari Malang jalan darat dua jam ke Blitar. Di situ, ia melihat rakyat berjejal di pinggir jalan, menangis menjerit-jerit, atau diam terpaku dengan air mata bercucuran.
Bambang yang duduk dekat Rachma tak kuasa menahan haru demi melihat begitu besar kecintaan rakyat kepada Bung Karno. Ia pun berkata pelan kepada Rachma, “Lihatlah, Rachma, rakyat masih mencintai Bung Karno. Mereka juga merasa kehilangan. Jasa bapak bagi nusa dan bangsa ini tidak akan terlupakan selamanya.” Rachma mengangguk.
Pemandangan yang sama tampak di Blitar hingga ke areal pemakaman. Ratusan ribu rakyat sudah menunggu. Bahkan militer harus ekstra ketat menjaga lautan manusia yang ingin merangsek mendekat, melihat, menyentuh peti jenazah Bung Karno.
Sementara itu, upacara pemakaman dengan cepat dilaksanakan. Panglima TNI Jenderal M. Panggabean menjadi inspektur upacara mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Prosesi pemakaman berlanjut. Peti jenazah pelan-pelan diturunkan ke liang kubur. Tak lama kemudian, liang kubur mulai ditutup timbunan tanah… saat itulah meledak tangis putra-putri Bung Karno, yang kemudian sisusul ledakan tangis pelayat yang lain di sekitar makam. Bambang Widjanarko merasa hancur hatinya demi melihat penderitaan anak-anak Bung Karno ditinggal pergi bapaknya untuk selama-lamanya. Tanpa terasa, air mata Bambang mengalir lagi di pipi.
Akhirnya, selesailah upacara pemakaman Bung Karno yang berlangsung sederhana tetapi khidmat. Acara pun ditutup tanpa menunggu selesainya peletakkan karangan bunga. Meski rombongan resmi sudah meninggalkan makam, tetapi ribuan manusia tak beranjak. Bahkan aliran peziarah dari berbagai penjuru negeri, terus mengalir hingga malam. Mereka maju berkelompok-kelompok, meletakkan karangan bunga atau menaburkan bunga lepas di tangannya, kemudian berjongkok, atau duduk memanjatkan doa, menangis di dekat pusara Bung Karno.

Malam makin gelap, tetapi sama sekali tak menyurutkan lautan manusia mengalir menuju makam Bung Karno. Makin malam, makin gelap, tampak makin khusuk mereka bedoa. Ratusan orang meletakkan karangan bunga, ratusan orang menabur bunga lepas, tetapi puluhan ribu pelayat pergi membawa segenggam bunga. Alhasil, karangan bunga dan taburan bunga yang menggunung si sore hari, telah habis diambil peziarah lain selagi matahari belum lagi merekah di ufuk timur. Habis bunga, peziarah berikutnya menjumput segenggam tanah di pusara Bung Karno, dan dimasukkan saku celana. Tak ayal, tanah menggunduk di atas jazad Bung Karno pun menjadi rata. Inilah dalam ritual Jawa yang disebut “ngalap berkah”.
Seorang pelayat, dan ia adalah rakyat biasa, berkata, “Bung Karno adalah seorang pemimpin besar, Pak. Kami rakyat, sangat mencintainya. Sebagai kenangan saya bawa pulang sedikit bunga ini.”
Begitulah, karangan bunga, taburan bunga, bahkan gundukan tanah pun dijumput para peziarah. Yang tampak keesokan harinya, 23 Juni 1970 adalah pusara berhias tanah merah. Merah menyalakan semangat tiada padam. Biarpun jazad terkubur dalam tanah, semangat tak akan lekang dimakan waktu. Biar jazad hancur menyatu dengan tanah, tapi kobaran semangat perjuangan tetap menyala. Sukarno hanya mati jazad, namun ruh dan jiwanya tetap menyatu dengan rakyat. Hidup dan terus mewarnai semangat juang rakyat.
Manusia Sukarno telah tiada. Putra Sang Fajar yang lahir tatkala surya mulai bersinar, telah kembali dalam pelukan bumi Nusantara yang sangat ia cintai. Ia masuk pelukan bumi ketika matahari condong ke barat, menuju peraduan malam. Begitulah matahari bersinar dan tenggelam setiap hari. Begitulah manusia lahir dan mati. Namun bagi bangsa Indonesia, nama Bung Karno akan tetap dikenang, diingat karena perjuangannya, pengabdiannya, dan pengorbanannya yang dengan sepenuh hati telah ia baktikan.

Rakyat Indonesia dari penjuru Tanah Air, berjubel, tidak saja di sekitar Wisma Yaso tempat jenazah Bung Karno disemayamkan, tetapi juga di Blitar, Jawa Timur, tempat jazad Bung Karno dikebumikan. Seperti pengalaman pribadi mantan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko. Ia merasa bagai tersambar petis demi mendengar kematian tokoh bangsa yang delapan tahun ia layani. Bambang yang ketika Bung Karno wafat sudah menjabat sebagai Asisten Kepala Personil Urusan Militer Mabes TNI-AL itu, bergegas menuju Wisma Yaso.
Wisma Yaso yang sejak siang sudah dijejali kerumunan rakyat yang hendak melayat, tidak juga surut hingga malam hari. Bambang pun masuk dalam antrian pelayat, yang berjalan menuju ruang tengah Wisma Yaso setapak demi setapak. Suasana ketika itu dilukiskan sebagai sangat mengharukan. Tidak terdengar percakapan, kecuali isak tangis, dan bisik-bisik pelayat. Di sudut ruang, masih tampak kerabat dan pelayat yang tak kuasa menahan jeritan hati yang mendesak di rongga dada, hingga tampak tersedu-sedu.
Tiba di dekat peti jenazah, Bambang melantunkan doa, “Ya Tuhan, Engkau telah berkenan memanggil kembali putraMu, Bung Karno. Terimalah kiranya arwah beliau di sisiMu. Sudilah Engkau mengampuni segala dosa-dosanya dan berkenanlah Engkau menerima segala tekad dan perbuatannya yang baik. Engkau Mahatahu ya Tuhan, dan Engkaulah Mahakuasa, aku mohon kabulkanlah doaku ini. Amin”
Segera setelah usai berdoa, Bambang menuju kamar lain, tempat keluarga BK berkumpul. Di sana tampak Hartini, Dewi, Guntur, Mega, Rachma, Sukma, Guruh, Bayu, dan Taufan. Mereka pun saling berangkulan. Sejurus kemudian, Sekmil Presiden, Tjokropranolo mendekati Bambang dan berkata, “Mas Bambang, kami mohon sedapatnya bantulah kami dalam menjaga dan melayani keluarga BK yang saat ini amat sedih dan emosional.” Bambang segera menukas, “Baik, tapi toong sampaikan hal ini kepada KSAL.”
Begitulah. Bambang sejak itu tak pernah jauh dari keluarga Bung Karno. Baginya, inilah bhakti terakhir yang dapat ia persembahkan bagi Bung Karno. Bambang juga berada di mobil bersama keluarga Bung Karno dalam perjalanan dari Wisma Yaso ke Halim, dari Halim terbang ke Malang, dan dari Malang jalan darat dua jam ke Blitar. Di situ, ia melihat rakyat berjejal di pinggir jalan, menangis menjerit-jerit, atau diam terpaku dengan air mata bercucuran.
Bambang yang duduk dekat Rachma tak kuasa menahan haru demi melihat begitu besar kecintaan rakyat kepada Bung Karno. Ia pun berkata pelan kepada Rachma, “Lihatlah, Rachma, rakyat masih mencintai Bung Karno. Mereka juga merasa kehilangan. Jasa bapak bagi nusa dan bangsa ini tidak akan terlupakan selamanya.” Rachma mengangguk.
Pemandangan yang sama tampak di Blitar hingga ke areal pemakaman. Ratusan ribu rakyat sudah menunggu. Bahkan militer harus ekstra ketat menjaga lautan manusia yang ingin merangsek mendekat, melihat, menyentuh peti jenazah Bung Karno.
Sementara itu, upacara pemakaman dengan cepat dilaksanakan. Panglima TNI Jenderal M. Panggabean menjadi inspektur upacara mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Prosesi pemakaman berlanjut. Peti jenazah pelan-pelan diturunkan ke liang kubur. Tak lama kemudian, liang kubur mulai ditutup timbunan tanah… saat itulah meledak tangis putra-putri Bung Karno, yang kemudian sisusul ledakan tangis pelayat yang lain di sekitar makam. Bambang Widjanarko merasa hancur hatinya demi melihat penderitaan anak-anak Bung Karno ditinggal pergi bapaknya untuk selama-lamanya. Tanpa terasa, air mata Bambang mengalir lagi di pipi.
Akhirnya, selesailah upacara pemakaman Bung Karno yang berlangsung sederhana tetapi khidmat. Acara pun ditutup tanpa menunggu selesainya peletakkan karangan bunga. Meski rombongan resmi sudah meninggalkan makam, tetapi ribuan manusia tak beranjak. Bahkan aliran peziarah dari berbagai penjuru negeri, terus mengalir hingga malam. Mereka maju berkelompok-kelompok, meletakkan karangan bunga atau menaburkan bunga lepas di tangannya, kemudian berjongkok, atau duduk memanjatkan doa, menangis di dekat pusara Bung Karno.

Malam makin gelap, tetapi sama sekali tak menyurutkan lautan manusia mengalir menuju makam Bung Karno. Makin malam, makin gelap, tampak makin khusuk mereka bedoa. Ratusan orang meletakkan karangan bunga, ratusan orang menabur bunga lepas, tetapi puluhan ribu pelayat pergi membawa segenggam bunga. Alhasil, karangan bunga dan taburan bunga yang menggunung si sore hari, telah habis diambil peziarah lain selagi matahari belum lagi merekah di ufuk timur. Habis bunga, peziarah berikutnya menjumput segenggam tanah di pusara Bung Karno, dan dimasukkan saku celana. Tak ayal, tanah menggunduk di atas jazad Bung Karno pun menjadi rata. Inilah dalam ritual Jawa yang disebut “ngalap berkah”.
Seorang pelayat, dan ia adalah rakyat biasa, berkata, “Bung Karno adalah seorang pemimpin besar, Pak. Kami rakyat, sangat mencintainya. Sebagai kenangan saya bawa pulang sedikit bunga ini.”
Begitulah, karangan bunga, taburan bunga, bahkan gundukan tanah pun dijumput para peziarah. Yang tampak keesokan harinya, 23 Juni 1970 adalah pusara berhias tanah merah. Merah menyalakan semangat tiada padam. Biarpun jazad terkubur dalam tanah, semangat tak akan lekang dimakan waktu. Biar jazad hancur menyatu dengan tanah, tapi kobaran semangat perjuangan tetap menyala. Sukarno hanya mati jazad, namun ruh dan jiwanya tetap menyatu dengan rakyat. Hidup dan terus mewarnai semangat juang rakyat.
Manusia Sukarno telah tiada. Putra Sang Fajar yang lahir tatkala surya mulai bersinar, telah kembali dalam pelukan bumi Nusantara yang sangat ia cintai. Ia masuk pelukan bumi ketika matahari condong ke barat, menuju peraduan malam. Begitulah matahari bersinar dan tenggelam setiap hari. Begitulah manusia lahir dan mati. Namun bagi bangsa Indonesia, nama Bung Karno akan tetap dikenang, diingat karena perjuangannya, pengabdiannya, dan pengorbanannya yang dengan sepenuh hati telah ia baktikan.
Sumber

